- Akademizi Dampingi Audit Syariah untuk LAZ Ulil Albab
- BAZNAS Luncurkan 29 Program Ramadan
- BAZNAS dan Media Kolaborasi Perkuat Literasi Zakat
- Tagline Ramadan BAZNAS RI “Zakat Menguatkan Indonesia”
- Kemenimipas Bantu Penyintas Banjir di Padang
- Lazismu Terapkan Tata Kelola Profesional Zakat Produktif
- Lazismu Jember Perkuat Kolaborasi Penghimpunan
- Masjid PB Soedirman dan Lazismu Galang Dana untuk Sumatra
- Zakat Sukses dan PT Agrinas Bantu Penyintas Banjir Cilegon
- Komunitas Musik Indie Bantu Sumatra via DD
Zakat Penghabisan di Bulan Kemerdekaan
Oleh: Yasyfa Raisza

Keterangan Gambar : Foto: Asisten AI
Kota itu berwarna merah putih sejak minggu pertama Agustus.
Bendera kecil berkibar di pagar rumah, baliho politisi menumpuk di setiap
tikungan, dan spanduk bertuliskan “Zakat untuk Negeri, Iman untuk
Kemerdekaan” menggantung di depan kantor Badan Amil Zakat daerah.
Di balik spanduk itu, Arif duduk di balik meja kerjanya yang
dingin dan rapi, mengetik laporan penyaluran zakat kuartal kedua. Seharusnya
pekerjaannya sederhana—menghitung, mencatat, menyalurkan. Tapi sejak “Program
Zakat Kemerdekaan” diluncurkan oleh lembaga itu, semuanya jadi pelik.
“Jangan lupa, laporan terakhir harus disetujui langsung sama
Bu Ratna,” kata Yani, rekan kerjanya, sambil menumpuk berkas setebal
ensiklopedia di meja Arif.
Baca Lainnya :
- Jalan Pulang Seorang Ayah0
- Di Balik Ayat yang Tak Selesai0
- Iman yang Tak Tenggelam Dalam Arus 0
- Luka yang Tak Terlihat0
- Warisan Terakhir Nenek Rahmah0
Bu Ratna bukan hanya kepala lembaga zakat itu. Ia juga istri
calon wali kota, Pak Haryo, yang sedang gencar berkampanye lewat jargon “Kemerdekaan
Ekonomi Umat.” Dan “Program Zakat Kemerdekaan” itu hanyalah satu dari
sekian proyek pencitraan yang diluncurkan di bulan ini.
Arif tahu, sebagian zakat yang dikumpulkan bulan lalu belum
disalurkan. Dana itu “ditunda” dengan alasan administratif—setidaknya begitu
tertulis di laporan internal. Tapi desas-desus di antara staf menyebut,
sebagian besar dana itu diarahkan untuk mendanai acara “Gerakan Sedekah
Merdeka” yang kebetulan dihadiri langsung oleh Pak Haryo dan disiarkan di
televisi lokal.
“Katanya sih demi transparansi publik,” gumam Arif saat
menandatangani formulir permintaan logistik acara. “Tapi kenapa harus pakai
uang umat buat spanduk dan tenda megah?”
Yani cuma mengangkat bahu. “Kamu kebanyakan mikir, Rif. Ini
perintah dari atas. Kita cuma staf.”
Arif menghela napas. Ia sudah lima tahun bekerja di lembaga
itu, dan baru kali ini ia merasa pekerjaannya lebih mirip alat politik daripada
ladang amal. Tapi siapa dia, hanya pegawai biasa dengan gaji pas-pasan dan
cicilan motor yang belum lunas.
Malamnya, di warung kopi dekat rumah kontrakannya, Arif
bertemu dengan Dimas, sahabat lamanya sejak kuliah. Dimas kini bekerja sebagai
wartawan di media lokal.
“Lu tahu gak, Rif,” kata Dimas setelah menyeruput kopi
hitam. “Gue lagi dapat bocoran soal dana zakat di lembaga lu. Katanya
disalurkan ke kegiatan kampanye terselubung. Bener gak?”
Arif terdiam. Matanya menatap kopi yang mulai dingin.
“Gue gak bisa ngomong apa-apa, Mas,” jawabnya pelan.
Dimas tersenyum miring. “Gak bisa ngomong, atau gak berani
ngomong?”
Pertanyaan itu menancap di kepala Arif sampai larut malam.
Ia pulang ke kontrakan, menatap layar laptop yang masih menampilkan laporan
keuangan lembaganya. Ada angka-angka yang tidak seimbang, tanda-tanda transfer
ke rekening pihak ketiga, dan nama-nama yang tak dikenal di daftar penerima
manfaat.
Ia menutup laptopnya, tapi pikirannya tak mau diam.
Dua hari kemudian, kantor lembaga zakat penuh sesak. Ada tim
kampanye Pak Haryo yang datang, ada panitia dari Pemkot, dan ada juga kru
televisi. Semua sibuk menyiapkan acara besar: "Penyerahan Zakat Terakhir di
Bulan Kemerdekaan".
Bu Ratna memerintahkan semua staf mengenakan batik merah
putih. Ia sendiri mengenakan jilbab merah marun dan bros emas berbentuk garuda.
Senyumnya lebar, tapi tajam.
“Arif,” panggilnya dengan suara lembut namun tegas.
“Pastikan daftar penerima sudah siap. Saya mau semua terlihat rapi di depan
kamera. Jangan sampai ada kesalahan data.”
“Baik, Bu,” jawab Arif singkat.
Namun ketika ia memeriksa ulang data penerima, ia menemukan
sesuatu yang janggal. Nama-nama penerima di daftar utama bukan warga miskin
binaan lembaga itu, melainkan relawan dan simpatisan partai Pak Haryo. Beberapa
bahkan tercatat sebagai pengusaha kecil yang bukan mustahik.
Arif menatap layar monitor lama itu lama sekali. Ia merasa
seperti baru saja menelan sesuatu yang getir.
Ketika acara dimulai, musik marawis bergema, kamera televisi
berputar, dan Pak Haryo naik ke panggung sambil tersenyum di depan mikrofon.
“Zakat adalah bentuk cinta kita kepada negeri ini,” katanya
lantang. “Kita buktikan bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika umat saling
menolong.”
Tepuk tangan menggema.
Arif berdiri di pinggir ruangan, menyaksikan amplop-amplop
putih dibagikan dengan simbolis. Di layar proyektor terpampang tulisan: ‘Zakat
Terakhir di Bulan Kemerdekaan: Bersama Menuju Umat Mandiri.’
Sementara itu, Dimas mengirim pesan lewat ponsel Arif:
“Rif, kalau mau bantu umat beneran, kasih gue bukti. Satu
dokumen aja cukup.”
Arif menggenggam ponselnya erat-erat. Keringat dingin
mengalir di pelipis. Ia tahu kalau ia kirim dokumen itu, lembaga bisa
terguncang, Bu Ratna bisa kehilangan jabatannya, dan ia sendiri bisa dipecat.
Tapi kalau ia diam, kebohongan itu akan terus disiarkan ke publik sebagai
kebenaran.
Sore harinya, setelah acara selesai, Bu Ratna memanggilnya
ke ruangan.
“Kamu terlihat tegang, Arif,” katanya sambil menyesap teh.
“Ada masalah?”
“Tidak, Bu.”
“Saya tahu kamu anak yang jujur,” lanjut Bu Ratna,
menatapnya tajam. “Tapi kamu juga harus tahu, kadang kebaikan itu perlu
strategi. Kalau kita terlalu lurus, kita bisa patah. Paham maksud saya?”
Arif hanya mengangguk pelan.
Bu Ratna tersenyum kecil. “Kita ini sedang berjuang demi
umat. Jangan terlalu banyak idealisme. Dunia ini butuh orang realistis.”
Kata-kata itu menempel di kepala Arif bahkan setelah ia
keluar dari ruangan. Di koridor, ia berpapasan dengan staf logistik yang
membawa tumpukan amplop. Di setiap amplop, ada logo lembaga zakat dan wajah Pak
Haryo tersenyum dengan tulisan kecil: “Untuk Kemerdekaan Ekonomi Umat.”
Malamnya, Arif duduk di meja kerja sempitnya di kontrakan.
Di layar laptop, laporan keuangan lembaga masih terbuka. Jari-jarinya gemetar
di atas tombol Print.
Sementara di ponselnya, pesan dari Dimas menunggu:
“Kalau gak sekarang, semuanya akan hilang jejak. Gue tahu
kamu masih punya nurani, Rif.”
Arif menatap layar, lalu menatap jendela. Di luar, suara
kembang api kecil terdengar—mungkin anak-anak sedang latihan lomba tujuh
belasan. Di langit, warna merah dan putih berkedip dalam percikan cahaya.
Ia menarik napas panjang.
Lalu menekan tombol Print.
Kertas demi kertas keluar dari printer murahan di sudut
meja. Angka-angka, tanda tangan, dan cap lembaga itu kini ada di tangannya.
Bukti.
Namun ketika ia hendak memotret dan mengirimkan berkas itu
pada Dimas, pintu kontrakannya diketuk keras dari luar.
Tok. Tok. Tok.
“Arif! Ada tamu dari kantor!”
Suara itu milik Yani. Tapi di belakangnya, ia mendengar
suara lain—lebih berat, lebih resmi.
Arif menatap printer yang masih menyala, lalu menatap
tumpukan dokumen di tangannya.
Apakah ia akan membuka pintu, atau menyembunyikan kebenaran
itu selamanya?
“Arif, buka pintunya! Cepat!”
Suara Yani terdengar panik. Arif menatap gagang pintu yang
bergetar karena ketukan yang makin keras.
“Sebentar!” teriaknya, pura-pura sibuk. Ia segera
menyembunyikan tumpukan dokumen itu ke dalam jaket usang di lemari. Printer
masih menyala, lampu indikatornya berkedip.
Ketika ia membuka pintu, dua orang berseragam berdiri di
belakang Yani. Salah satunya membawa map coklat, satunya lagi memakai jas
dengan pin logo lembaga zakat di dada.
“Maaf mengganggu malam-malam, Mas Arif,” kata pria berjas
itu dengan senyum tipis. “Bu Ratna minta beberapa dokumen keuangan yang belum
dikumpulkan. Ada file laporan internal di komputer Anda?”
Arif berusaha tersenyum. “Oh, iya, tapi datanya belum
lengkap. Lagi saya revisi.”
Pria itu menatap layar laptop di meja, lalu mengangguk
kecil. “Baik. Kami tunggu besok pagi di kantor, ya.”
Mereka pergi tanpa banyak bicara. Tapi sebelum menutup
pintu, Yani menatap Arif lama—tatapan campuran antara cemas dan iba.
Setelah pintu tertutup, Arif duduk di kursi dengan napas
tercekat. Ia tahu, mereka tidak benar-benar datang untuk meminta laporan.
Mereka sedang memeriksa apakah ada dokumen yang bocor keluar.
Arif menatap layar televisi kecil di ruang tunggu kantor. Ia
merasa mual.
Dimas menelepon pagi itu, suaranya cepat dan mendesak.
“Rif, gue tahu lu punya dokumennya. Tapi hati-hati, mereka
mulai ngawasin. Gue dapet kabar ada staf yang dicurigai bocorin data.”
Arif mematikan panggilan tanpa jawaban. Di sekelilingnya,
suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Semua staf bekerja dengan
suara pelan. Bu Ratna belum muncul, tapi kabarnya akan mengadakan rapat
tertutup siang nanti.
Arif menatap lemari arsip tempat ia menyimpan salinan
laporan itu. Hatinya bergolak—antara takut, marah, dan entah apa lagi.
“Teman-teman,” katanya, “kita sedang menghadapi situasi
sensitif. Ada isu liar di luar sana soal penyalahgunaan dana zakat. Saya harap
semua di sini loyal dan berhati-hati. Jangan sampai ada data keluar tanpa izin
saya.”
Tatapannya berputar, berhenti lama di wajah Arif.
Ia meneguk ludah, menunduk.
Rapat berakhir tanpa tepuk tangan, hanya keheningan. Arif
keluar paling akhir. Di lorong, ia kembali menerima pesan dari Dimas:
“Mereka akan tutup kasus ini sebelum upacara 17 Agustus.
Kalau gak sekarang, semuanya lenyap.”
Arif berjalan cepat ke ruang arsip, membuka lemari, dan
mengambil berkas. Ia menyalin semuanya ke flashdisk kecil. Tangannya gemetar
saat memasukkan ke saku celana.
Sore itu, ia keluar kantor dengan alasan “mengantar
laporan.”
Namun di parkiran, seseorang menepuk pundaknya.
“Ke mana, Mas Arif?” tanya suara bariton di belakangnya.
Pria berjas yang semalam datang ke kontrakannya kini berdiri di sana, tersenyum
dingin.
“Ke kantor pos, Pak,” jawab Arif terbata.
Pria itu menepuk bahunya pelan. “Hati-hati di jalan.
Sekarang banyak yang suka salah langkah.”
Senyum itu membuat Arif ingin muntah. Tapi ia tetap
melangkah pergi.
“Lu bawa?” tanya Dimas pelan.
Arif mengangguk, menyerahkan flashdisk itu dengan tangan
gemetar. “Jaga baik-baik. Gue gak tahu kalau ini ketahuan bakal jadi apa.”
Dimas mengangguk cepat. “Gue janji. Ini bukan cuma soal
berita. Ini soal kebenaran.”
Mereka berpisah tanpa kata.
“Mas Arif,” suara di ujung sana berat dan dingin. “Datang
besok ke kantor jam delapan pagi. Ada yang perlu dibicarakan.”
Telepon terputus.
Ia menatap layar ponselnya lama. Di luar, suara sirine
polisi melintas.
Bu Ratna berdiri di depan ruang rapat, wajahnya tampak lelah
namun tetap tegar. “Mas Arif,” katanya pelan, “ikut saya.”
Ia menuntunnya ke ruangannya. Di atas meja, ada surat
pengunduran diri yang sudah diketik rapi.
“Untuk kebaikan bersama,” ucapnya lembut. “Tanda tangani
ini, dan semuanya selesai. Tidak akan ada yang tahu apa-apa.”
Arif memandang kertas itu. Tangannya terasa dingin.
“Tapi, Bu... dana itu—”
“Sudah diurus,” potong Bu Ratna cepat. “Kita hanya membantu
masyarakat dengan cara yang berbeda. Jangan naif, Arif. Kalau kamu tanda
tangan, kamu aman. Kalau tidak...”
Ia tidak melanjutkan kalimat itu. Tapi tatapannya cukup
menjelaskan.
Arif menatap pena di atas meja. Dalam kepalanya, suara Dimas
bergema: “Ini soal kebenaran.”
Sementara di luar, suara sirine kembali terdengar.
Ia mengambil pena.
Lalu… berhenti.
Hari berganti cepat. Media lokal mendadak menayangkan berita mengejutkan: “Wartawan Ditemukan Tak Sadarkan Diri di Mobil, Diduga Korban Kecelakaan.”
Nama korban: Dimas Raharjo.
Arif terpaku di depan televisi. Flashdisk itu… hilang.
Beritanya hanya tayang sehari, lalu lenyap dari linimasa.
Di kantor, semua berjalan seperti biasa. Program zakat
berikutnya sudah disiapkan, kali ini bertajuk “Zakat Pahlawan Bangsa.”
Tak ada yang membicarakan Dimas. Tak ada yang membicarakan
dana itu lagi.
Ia memegang satu amplop putih yang tersisa dari acara tempo
hari. Di dalamnya, hanya ada uang seratus ribu rupiah dan brosur bergambar
wajah Pak Haryo tersenyum.
Ia menatap amplop itu lama, lalu melipatnya kecil-kecil.
Hujan rintik turun perlahan, membasahi tanah yang sudah
lelah menampung banyak janji.
Dari kejauhan, terdengar suara toa baru berbunyi:
“Selamat datang di era baru kemerdekaan ekonomi umat!”
Arif menatap langit yang kelabu.
Entah karena hujan, atau karena pikirannya yang kabur, ia
merasa seperti melihat sesuatu jatuh dari langit—mungkin kembang api terakhir
malam itu, atau mungkin sesuatu yang lain.
Amplop di tangannya mulai basah. Ia tidak tahu harus
diserahkan kepada siapa lagi.
Lalu ia berjalan pergi, menembus hujan, tanpa arah.
Keesokan paginya, kantor lembaga zakat dibuka seperti biasa.
Di meja Arif, hanya tersisa secangkir kopi dingin dan kertas laporan yang belum
ditandatangani.
Bu Ratna memeriksa meja itu sebentar, lalu berkata kepada
staf,
“Kalau Arif datang, bilang saya ingin bicara baik-baik.”
Tapi Arif tak pernah datang lagi.
Sementara itu, di media nasional, berita kecil muncul dua
hari kemudian—singkat, tanpa nama jurnalis:
“Dokumen internal terkait dugaan penyalahgunaan dana
zakat daerah beredar anonim di dunia maya. Belum ada konfirmasi resmi dari
pihak berwenang.”
Tak ada yang tahu siapa yang mengunggahnya.
Di antara percikan kembang api yang tersisa di langit Agustus, mungkin kemerdekaan memang tak pernah selesai diperjuangkan. Tapi kali ini, tak ada pahlawan, tak ada penjahat—hanya seseorang yang akhirnya memilih diam di antara dua kebenaran yang saling meniadakan. ***



1.png)
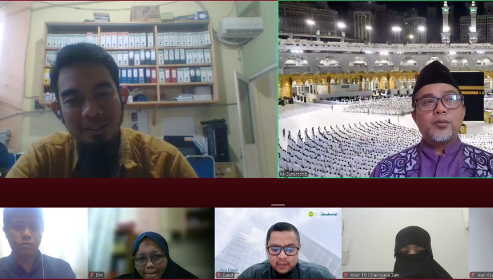






.jpg)
.png)
.png)