- Akademizi Dampingi Audit Syariah untuk LAZ Ulil Albab
- BAZNAS Luncurkan 29 Program Ramadan
- BAZNAS dan Media Kolaborasi Perkuat Literasi Zakat
- Tagline Ramadan BAZNAS RI “Zakat Menguatkan Indonesia”
- Kemenimipas Bantu Penyintas Banjir di Padang
- Lazismu Terapkan Tata Kelola Profesional Zakat Produktif
- Lazismu Jember Perkuat Kolaborasi Penghimpunan
- Masjid PB Soedirman dan Lazismu Galang Dana untuk Sumatra
- Zakat Sukses dan PT Agrinas Bantu Penyintas Banjir Cilegon
- Komunitas Musik Indie Bantu Sumatra via DD
Di Balik Ayat yang Tak Selesai
Yasyfa Raisza

Keterangan Gambar : Foto: Dok. Asissten AI
Suara azan Subuh dari menara Pondok Tahfidz Al-Mahfudz
menggema hingga ke gang-gang sempit Kampung Mijen, Semarang. Udara dingin
bercampur wangi tanah basah menyelinap masuk lewat jendela kamar yang sempit, berisi tiga ranjang tingkat. Di salah satu ranjang itu, Arkan membuka mata dengan
pelan. Matanya masih berat, tapi ia tahu, ini bukan hari biasa.
Hari ini adalah seleksi penerima Beasiswa Penghafal Al-Quran
Kota Semarang diadakan. Hanya dua orang saja yang akan dipilih dari seluruh
pesantren di kota itu. Beasiswa yang katanya bisa mengubah masa depan: biaya
hidup, kuliah, bahkan tiket umrah. Semua santri di Al-Mahfudz membicarakannya
selama berminggu-minggu.
Arkan duduk, merapikan pecinya, lalu menatap rak kayu di
depannya. Di sana, mushaf kecil berwarna hijau kusam tergeletak di antara
tumpukan kitab kuning. Mushaf itu sudah using, beberapa halamannya mulai
menguning dan beberapa lainnya robek di tepi. Tapi bagi Arkan, itu bukan hanya sekadar
kitab tapi itu juga sebagian dari dirinya.
Baca Lainnya :
- Iman yang Tak Tenggelam Dalam Arus 0
- Luka yang Tak Terlihat0
- Warisan Terakhir Nenek Rahmah0
- Dentang Terakhir Telegraf0
- Kepak Sayap Berbagi Komunitas Filantropi 0
Di bawah ranjang, Fadhil, sahabat sekamarnya, masih
terlelap.
“Dil,” panggil Arkan pelan. “Bangun, nanti ketinggalan subuh berjamaah.”
Fadhil menggeliat malas, lalu setengah membuka mata.
“Kalau bukan karena beasiswa itu, kamu juga nggak akan sekencang ini
hafalannya, Kan,” katanya, setengah menggoda.
Arkan tersenyum kecil. “Kalau rezeki, nggak akan ke mana, kan?”
“Tapi kalau rezeki direbut orang?” balas Fadhil, kali ini dengan nada datar.
Arkan tidak menanggapi. Ia tahu maksud kata-kata itu. Fadhil
juga ikut seleksi hari ini. Pagi menjelang, aula utama pondok dipenuhi para
santri yang menunggu giliran wawancara. Panitia dari Dinas Keagamaan Kota
Semarang datang dengan jas resmi, papan nama, dan senyum yang terlalu formal.
Di belakang mereka, spanduk besar bertuliskan “Program Beasiswa Hafidz al-Quran
Kota Semarang 1447 H Dalam Rangka Hari
Santri Nasional” tergantung dengan megah.
Arkan menggenggam map birunya erat. Di dalamnya ada surat
rekomendasi dari Kiai Mahfuz, pengasuh pondok.
Surat itu penting bahkan lebih penting dari hafalan. Tanpa rekomendasi kyai,
seorang santri tidak akan dilirik panitia.
“Nomor 17, Arkan bin Mulyadi,” panggil panitia.
Ia melangkah masuk ke ruang wawancara. Di sana ada tiga
orang juri: dua dari dinas, satu dari pondok besar lain. Di tengah ruangan,
duduk Ustaz Fauzi, guru tahfiznya, yang sejak dulu dikenal dingin dan sulit
ditebak.
“Baca Surat al-Mulk ayat 1 sampai 10,” perintah juri pertama.
Suara Arkan bergetar pelan di awal, tapi kemudian mengalun lembut dan stabil.
Ia menutup matanya, seolah setiap ayat menuntunnya pada ketenangan.
Ketika selesai, juri kedua mencatat sesuatu.
“Bagus. Tapi kenapa surat rekomendasi dari Kiai Mahfuz tidak ada tanda tangan
langsung? Hanya cap stempel.”
Arkan tertegun. “Tanda tangannya... belum sempat, Pak. Kiai
sedang di luar kota.”
Ustaz Fauzi mengangkat alis, “Saya lihat Fadhil sudah bawa tanda tangan asli.
Kamu lupa meminta, atau... memang tidak dikasih?”
Arkan menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa.
Malam itu, setelah isya, Arkan mendatangi kantor
administrasi pondok. Ia ingin memastikan surat rekomendasinya. Di balik pintu
kayu, ia mendengar suara dua orang berbicara pelan. Salah satunya suara Ustaz
Fauzi, satunya lagi Fadhil.
“Kamu sudah saya bantu. Surat rekomendasi Kiai Mahfuz saya
yang urus langsung. Tapi kamu tahu, beasiswa itu cuma dua. Kalau kamu mau aman,
jangan kasih tahu Arkan soal ini,” kata Ustaz Fauzi.
Fadhil terdiam lama. “Tapi, ustaz... dia hafalannya lebih
kuat dari saya.”
“Itu bukan soal hafalan, Fadhil. Ini soal loyalitas. Saya tahu siapa yang
pantas.”
Langkah Arkan terhenti di luar pintu. Jantungnya berdetak
keras. Ia menelan ludah, mencoba memastikan apa yang baru saja didengarnya
bukan salah paham. Tapi ketika Fadhil keluar dan menundukkan wajah tanpa berani
menatapnya, semuanya jelas.
Malam itu, Arkan tidak tidur. Ia hanya menatap langitlangit
kamar, mendengarkan detik jam berdetak seperti ayat-ayat yang menggantung di
kepalanya. Ia ingin marah. Tapi pada siapa?
Tiga hari kemudian, seluruh santri dikumpulkan di halaman
utama pondok. Spanduk besar berganti tulisan: “Penyaluran Beasiswa untuk
Penghafal al-Quran — Dalam Rangka Hari Santri Nasional”.
Wali kota Semarang datang, lengkap dengan rombongan dan wartawan. Kamera
menyorot ke panggung tempat dua nama akan diumumkan.
“Penerima Beasiswa Penghafal al-Quran Tahun Ini,” suara
panitia menggema lewat pengeras suara, “adalah... Fadhil Ahmad dari Pondok al-Mahfuz,
dan Lukman Hadi dari Pondok Darul Furqan!”
Sorak sorai santri menggema. Fadhil berdiri kaku, menatap ke
arah Arkan yang duduk di barisan tengah. Tatapan mereka bertemu hanya
sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat dada Arkan sesak.
Ustaz Fauzi berdiri di samping panggung, tersenyum tipis.
Arkan menunduk, menggenggam mushaf hijau tuanya. Suara gemuruh tepuk tangan
seperti jauh, samar, seolah datang dari dunia lain.
Malamnya, Arkan menerima kabar dari rumah: ibunya jatuh
sakit. Uang kiriman dari pondok belum dikirim karena ia tidak jadi menerima
beasiswa internal. Ia meminta izin pulang sebentar.
Di rumah kecil di daerah Pedurungan, ibunya terbaring lemah.
“Nggak apaapa, Nak,” katanya dengan suara pelan. “Ibu cuma pusing sedikit.”
Arkan menatap wajah ibunya yang pucat. Di meja, ada amplop surat dari pihak
pondok.
Ketika dibuka, isinya membuatnya terdiam:
“Mohon maaf, karena berkas saudara tidak lengkap dan surat rekomendasi
dianggap tidak sah, Anda tidak memenuhi syarat untuk seleksi tahun ini.”
Di pojok amplop, ada tanda tangan kecil: Ustaz Fauzi.
Seminggu kemudian, Arkan kembali ke pondok. Ia tidak datang
ke kelas. Ia hanya duduk di serambi mushala, menatap halaman pondok yang mulai
kosong. Beberapa santri sedang bersiap untuk acara penyaluran tahap kedua.
Fadhil terlihat sibuk membantu panitia, wajahnya terlihat resah.
“Kan,” Fadhil menghampirinya. “Aku mau ngomong.”
Arkan tidak menoleh.
“Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi... semua ini salah. Aku dengar kamu dikeluarkan dari daftar cadangan. Aku coba klarifikasi ke ustaz, tapi”
“Sudah, Dil,” potong Arkan pelan. “Aku tahu.”
Fadhil menunduk. “Aku nggak bermaksud nyakitin kamu.”
“Kalau kamu nggak bermaksud, kenapa diam waktu tahu?”
Fadhil terdiam lama. “Karena aku takut. Beasiswa ini satusatunya cara aku
keluar dari sini.”
Arkan tersenyum getir. “Dan kamu pikir aku nggak takut?”
Seminggu setelah acara Hari Santri, sebuah surat anonim
dikirim ke pihak dinas. Isinya: bukti foto percakapan antara Fadhil dan Ustaz
Fauzi tentang pemalsuan rekomendasi. Tidak ada nama pengirim, tapi tulisan di
amplop itu mirip tulisan tangan Arkan.
Kabar itu menyebar cepat. Ustaz Fauzi dipanggil ke ruang
kyai. Beberapa hari kemudian, ia tidak terlihat lagi di pondok. Santrisantri
berbisik, katanya dipindahkan ke pondok lain untuk “menghindari polemik.”
Fadhil pun dipanggil. Beasiswanya ditunda sampai
penyelidikan selesai.
Sejak itu, pondok sepi dari kabar gembira.
Suatu malam, Arkan kembali ke mushaf hijau tuanya. Ia membuka halaman yang sobek di bagian Surah al-Mulk. Di situ, hanya setengah ayat yang masih terbaca.
"Tabaarakallazi biyadihilmulku wa huwa ‘ala kulli syai’in qadiir..."
Lalu robek.
Ia menatap bagian yang hilang lama sekali. Mungkin, seperti
itulah dirinya sekarang — kehilangan bagian penting, tapi tetap utuh di luar.
Di luar kamar, suara hujan turun perlahan. Fadhil mengetuk pintu, membawa payung kecil.
“Kan, boleh aku duduk?”
Arkan mengangguk pelan. Mereka diam lama, hanya mendengarkan hujan.
“Aku tahu kamu yang kirim surat ke dinas,” kata Fadhil akhirnya.
Arkan menatapnya tanpa menjawab.
“Aku nggak marah. Mungkin memang harus begitu.”
Arkan tersenyum samar. “Kita cuma melakukan apa yang kita
anggap benar, ya?”
Fadhil menatap lantai. “Aku cuma ingin kamu tahu... kalau bukan karena aku,
mungkin ustaz tetap akan main curang. Aku hanya alat.”
“Semua orang alat bagi sesuatu,” jawab Arkan tenang. “Cuma kadang, kita nggak tahu siapa yang menggenggamnya.”
Malam semakin larut. Listrik di pondok tibatiba padam. Hanya
cahaya kecil dari lilin yang menyala di dekat mereka.
Fadhil menatap wajah Arkan yang tenang, tapi di matanya ada sesuatu yang tak
bisa dijelaskan — bukan marah, bukan benci, tapi semacam kehilangan.
“Besok aku mau keluar pondok,” kata Fadhil lirih.
“Beasiswaku dicabut.”
Arkan tidak menjawab.
“Lucu ya,” lanjut Fadhil pahit. “Kita sama-sama hafal al-Quran, tapi malah saling
menjatuhkan.”
Arkan menutup mushafnya perlahan. “Ayat bisa dihafal, Dil. Tapi nggak semua
orang bisa menanggung artinya.”
Hujan makin deras, menenggelamkan sisa percakapan mereka
malam itu.
Sebulan kemudian, dinas mengeluarkan pengumuman baru: beasiswa tahap tambahan untuk santri berprestasi tanpa rekomendasi pondok, hasil evaluasi ulang.
Di antara daftar itu, nama Arkan bin Mulyadi tertera di urutan pertama.
Tapi Arkan sudah tidak ada di pondok.
Kabar yang beredar: ia keluar diam-diam seminggu sebelumnya, setelah menerima
surat dari rumah — ibunya meninggal dunia.
Fadhil menemukan mushaf hijau itu di atas ranjang Arkan. Di
dalamnya, ada secarik kertas bertuliskan singkat:
“Ayat bisa hilang dari halaman, tapi tidak dari ingatan.”
Fadhil memandangi tulisan itu lama, sebelum akhirnya menutup
mushaf dan menyimpannya di dadanya sendiri.
Bertahuntahun kemudian, pada peringatan Hari Santri yang
lain, seorang qari muda tampil di Masjid Agung Semarang. Suaranya merdu,
tenang, dan mengalun dari ayat pertama Surah al-Mulk.
Di barisan belakang, seorang pria berpeci hitam menunduk,
menahan sesuatu di dadanya.
Di tangannya, mushaf hijau kusam masih tersimpan — dengan satu halaman yang
robek.
Dan di luar masjid, spanduk besar bertuliskan:
“Penyaluran Beasiswa Penghafal al-Quran — Dalam Rangka Hari Santri Nasional”
Cahaya lampu menyinari tulisan itu, tapi tak ada yang tahu
cerita di baliknya — karena sebagian kisah selalu hilang, seperti ayat yang tak
sempat diselesaikan.



1.png)
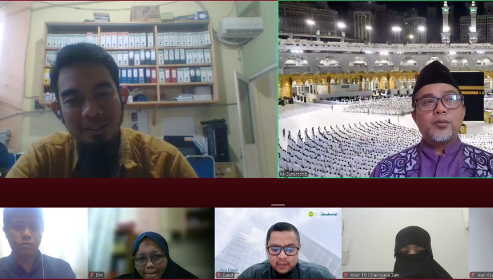






.jpg)
.png)
.png)