- IZI dan DKM Nurul Iman Salurkan Sembako Fidyah
- BAZNAS RI dan Artajasa Gelar Bazar Amal untuk Warga Prasejahtera
- IZI Kolaborasi dengan Bank Panin Dubai Syariah
- IZI Gelar Tarhib Ramadan di Cianjur
- Z-Talk BAZNAS RI Dorong “Zakat Menguatkan Indonesia”
- Ramadan 2026, BAZNAS Bidik Rp515 M
- BAZNAS RI Luncurkan 29 Program Ramadan
- BAZNAS RI Gandeng Media Perkuat Zakat untuk Pembangunan Nasional
- Ramadan Optimalkan Manfaat Zakat untuk Mustahik
- Tokoh Media: Zakat Instrumen Strategis Cegah Ketimpangan Sosial
Berkah yang Terselubung
Tiara Febi Nurkhaulah

Keterangan Gambar : Foto: Asistensi AI
Di sebuah kota kecil di pesisir Jawa,
hiduplah seorang pengusaha batik bernama Haji Karim. Usahanya besar, namanya
harum, dan rumahnya berdiri megah di tengah kota. Namun, di balik gemerlap
kehidupannya, ada sesuatu yang tak pernah ia sentuh: zakat dan sedekah.
“Usaha ini aku bangun dengan keringatku
sendiri,” gumamnya suatu malam sambil menghitung lembaran rupiah. “Kenapa harus
kuberikan kepada orang lain yang malas bekerja?”
Istrinya, Nyai Salma, sering menegur lembut.
Baca Lainnya :
- Air Mata di Balik Sedekah Seorang Nenek0
- Ketika Cinta Tanah Air Menjadi Sedekah untuk Bumi0
- Reinkarnasi Bandung Lautan Api0
- Tiga Malam untuk Selembar Merah Putih0
- Nasi Bungkus Lauk Mewah0
“Pak, rezeki itu titipan. Ada hak orang lain
di setiap keuntungan kita.”
Namun Karim selalu menutup telinga. Ia lebih
percaya pada kalkulatornya daripada pada janji Allah.
Di sudut lain kota, hiduplah seorang penjual
nasi uduk bernama Murni. Ia janda dengan dua anak kecil. Sejak suaminya
meninggal karena kecelakaan, ia berjuang keras menafkahi keluarga. Namun
penghasilannya tak pernah cukup, apalagi ketika putra bungsunya, Rafi, divonis
menderita penyakit jantung bawaan.
Suatu malam, Rafi kejang di rumah. Murni
panik membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata tegas:
“Anak ibu butuh operasi segera. Biayanya seratus juta rupiah.”
Bagaikan tersambar petir, Murni tak sanggup
berkata-kata. Seratus juta? Uang sebesar itu bahkan tak pernah ia lihat seumur
hidup.
Keesokan harinya, dengan hati penuh harap, Murni mendatangi rumah Haji Karim.
“Assalamualaikum, Haji. Saya mohon bantuan. Anak saya butuh operasi. Saya
dengar bapak orang yang sangat kaya dan dermawan.”
Karim menatapnya sinis.
“Dermawan? Itu cuma omongan orang. Aku tak
punya kewajiban membantu semua orang. Kalau kau mau uang, bekerjalah lebih
keras!”
Murni terdiam. Air matanya mengalir. Ia pamit
dengan langkah gontai, hatinya retak oleh penolakan itu.
Kabar penolakan Haji Karim menyebar cepat. Orang-orang mulai berbisik di pasar, di masjid, bahkan di warung kopi.
“Katanya kaya raya, tapi kikir luar biasa.”
“Lupa kalau harta itu titipan Allah.”
Nama Haji Karim yang dulu harum, kini jadi
ejekan.
Namun, puncak konflik terjadi ketika pabrik
batiknya kebakaran. Api melahap gudang utama, mesin-mesin mahal, bahkan stok
batik yang siap diekspor. Kerugian mencapai miliaran rupiah.
Karim berdiri di depan reruntuhan pabrik
dengan wajah pucat. Tangannya gemetar.
“Ya Allah… kenapa semua ini menimpaku?”
Malam itu, ia menangis tersedu di sajadah.
Hatinya mulai goyah.
Beberapa hari kemudian, ia mendatangi masjid. Di sana, ia melihat pengumuman tentang Lembaga Zakat dan Wakaf. Ustaz setempat berceramah:
“Siapa yang menafkahkan hartanya di jalan
Allah, tidak akan berkurang sedikit pun. Bahkan Allah akan melipatgandakan.
Sedekah itu penolak bala, penyejuk hati, dan penyambung persaudaraan.”
Kata-kata itu menusuk jantungnya. Untuk
pertama kali, ia merasa seluruh kesombongannya runtuh.
Keesokan harinya, Haji Karim memberanikan
diri mendatangi rumah Murni. Ia membawa sebuah amplop besar.
“Murni… maafkan aku. Dulu aku menolakmu
dengan sombong. Ini uang untuk operasi Rafi. Aku hanya berharap kau mau
memaafkan kebodohanku.”
Murni tertegun. Air matanya menetes deras.
“Pak Haji… ini lebih dari cukup. Saya… saya
tidak tahu harus berkata apa. Semoga Allah membalas kebaikan bapak.”
Pelukan haru pecah. Luka lama yang penuh
amarah dan kecewa, kini terobati dengan keikhlasan.
Beberapa bulan kemudian, Rafi berhasil
menjalani operasi dan sembuh. Sementara itu, meski usahanya belum pulih
sepenuhnya, Haji Karim merasa hatinya jauh lebih tenang. Ia mulai rutin
mengeluarkan zakat, membantu anak yatim, bahkan mewakafkan sebagian tanahnya
untuk pesantren.
Suatu hari, saat ia duduk di teras masjid
setelah salat Subuh, seorang sahabat menepuk pundaknya.
“Jadi inikah rahasia wajahmu sekarang selalu cerah, Ji? Bukan lagi batikmu yang
mewah, tapi sedekahmu yang membuatmu damai.”
Karim tersenyum.
“Aku baru sadar, harta yang sebenarnya bukan yang kusimpan di lemari besi, tapi yang kubagikan kepada orang lain. Karena itulah yang akan menemaniku kelak.”



1.png)




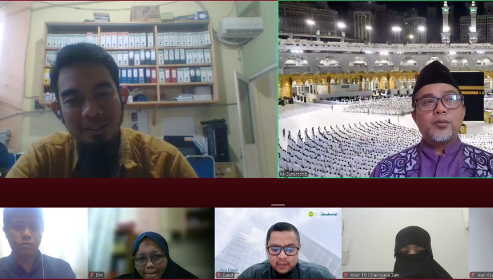


.jpg)
.png)
.png)