UIN Jakarta Salurkan Donasi Rp117 Juta bagi Korban Bencana
UIN Jakarta Salurkan Donasi Rp117 Juta bagi Korban Bencana
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta melalui Social Trust Fund (STF) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana di . . .




























.jpeg)







.jpg)
.png)
.png)














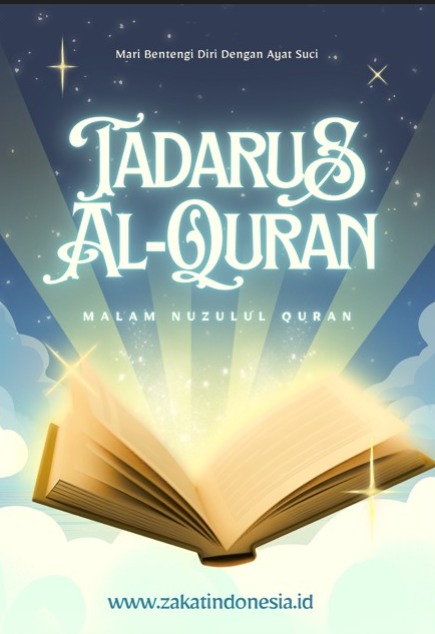







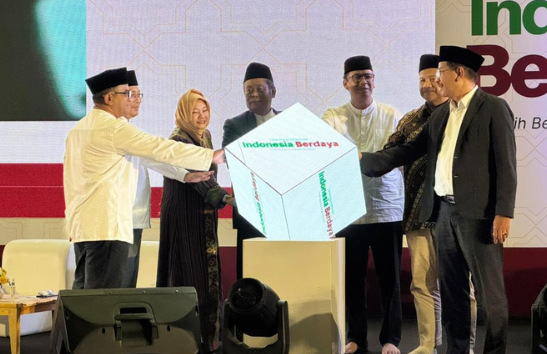



).png)





















